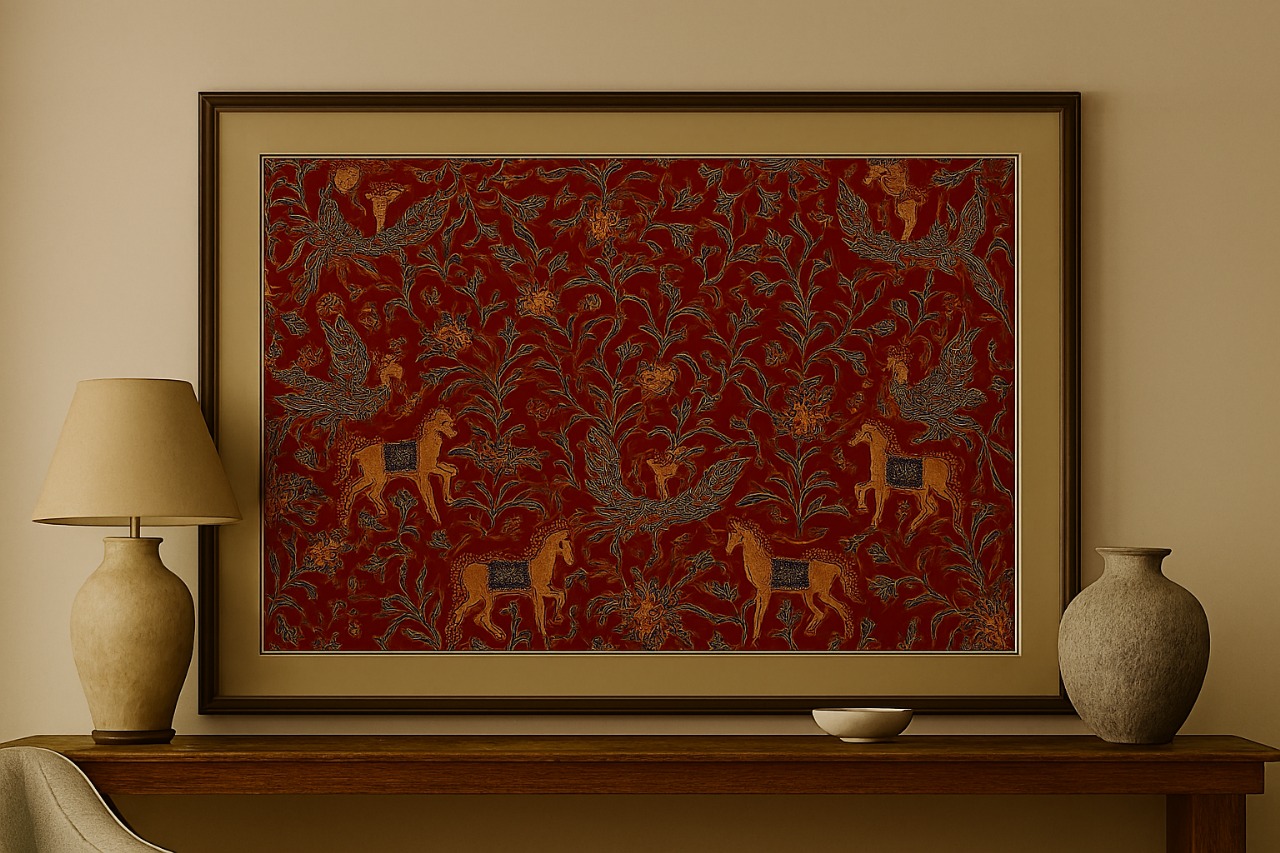Wayang Potehi: Warisan Tionghoa yang Masih Hidup di Jawa

Di tengah hiruk-pikuk kota besar dan derasnya arus modernisasi, masih ada seni tradisi yang bertahan dengan napas panjang: Wayang Potehi. Pertunjukan boneka kain asal Tiongkok ini telah menyeberangi lautan budaya dan menemukan rumah baru di tanah Jawa, khususnya di Surabaya dan Semarang. Lebih dari sekadar hiburan, Wayang Potehi menjadi jembatan yang menghubungkan dua kebudayaan besar—Tionghoa dan Jawa—dalam harmoni yang indah.
Jejak Sejarah dari Negeri Tirai Bambu
Asal-usul Wayang Potehi berakar dari Dinasti Jin di Tiongkok, sekitar abad ke-3 Masehi. Kata “potehi” sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yakni po (kain), te (kantong), dan hi (wayang atau pertunjukan). Artinya, pertunjukan boneka dari kain yang dimainkan di atas panggung kecil. Di masa lalu, pertunjukan ini sering digelar di kelenteng sebagai bagian dari ritual keagamaan untuk menghibur dewa-dewi dan memohon keberkahan.
Saat gelombang migrasi Tionghoa datang ke Nusantara, Wayang Potehi ikut berlayar menumpang kapal dagang menuju pelabuhan-pelabuhan besar di pesisir utara Jawa. Surabaya, Semarang, dan Lasem menjadi titik-titik penting penyebarannya. Para imigran membawa serta alat musik tradisional, boneka kain, dan kisah-kisah heroik dari daratan Tiongkok. Di tangan mereka, Wayang Potehi mulai beradaptasi dengan bahasa, musik, dan selera masyarakat lokal.
Adaptasi dan Akulturasi Budaya di Tanah Jawa
Perjalanan Wayang Potehi di Indonesia tidak selalu mudah. Pada masa awal, pertunjukan ini hanya ditampilkan di lingkungan komunitas Tionghoa dan menggunakan bahasa Hokkien. Namun, perlahan, pertunjukan ini mulai berbaur dengan budaya Jawa. Penonton pribumi yang penasaran ikut menonton, sementara para dalang lokal belajar mengoperasikan boneka dan menceritakan kisahnya dengan logat Jawa.
Dari sinilah akulturasi mulai terbentuk. Iringan musik tradisional Tionghoa berpadu dengan alat musik lokal seperti gamelan kecil dan kendang. Cerita-cerita klasik seperti “Sam Kok” atau “Sie Jin Kwie” dikisahkan ulang dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam dialek Jawa dan Madura. Boneka-boneka yang dulu berpakaian khas dinasti Tiongkok, kini kadang tampil dengan kostum bergaya lokal, tanpa kehilangan identitas asalnya.
Di Surabaya, misalnya, Wayang Potehi masih dapat dijumpai di Kelenteng Hong Tiek Hian, salah satu yang tertua di kota itu. Sementara di Semarang, Kelenteng Tay Kak Sie menjadi tempat berlangsungnya pertunjukan rutin, terutama saat perayaan Imlek atau Cap Go Meh. Dalam suasana penuh dupa dan cahaya lentera, boneka-boneka mungil itu bergerak lincah, menghidupkan kembali legenda kuno dalam bahasa yang kini akrab di telinga masyarakat Jawa.
Kisah-Kisah yang Mengandung Nilai Hidup
Setiap pertunjukan Wayang Potehi tidak hanya menawarkan cerita kepahlawanan, tetapi juga mengandung pesan moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kisah tentang kesetiaan, keberanian, dan kejujuran menjadi benang merah dari setiap lakon. Dalam satu pertunjukan, penonton bisa tertawa karena kelucuan tokoh badut, lalu tersentuh oleh perjuangan tokoh utama yang rela berkorban demi kebenaran.
Nilai-nilai ini yang membuat Wayang Potehi diterima lintas etnis dan generasi. Banyak penonton datang bukan hanya karena tertarik pada unsur budaya Tionghoa, melainkan karena merasa dekat dengan pesan yang disampaikan. Bagi masyarakat Jawa, Wayang Potehi terasa mirip dengan Wayang Kulit—keduanya sama-sama sarat filosofi dan refleksi kehidupan manusia.
Kebangkitan dari Senyap
Setelah mengalami masa kejayaan di tahun 1960-an, Wayang Potehi sempat nyaris menghilang pada era Orde Baru. Larangan terhadap segala bentuk ekspresi budaya Tionghoa membuat pertunjukan ini berhenti di banyak tempat. Namun, semangat para seniman tidak pernah padam. Beberapa dalang tua tetap mempertahankan tradisi ini secara sembunyi-sembunyi, sementara generasi berikutnya mulai mempelajari kembali dari sisa-sisa kenangan.
Kebangkitan Wayang Potehi mulai terlihat kembali setelah tahun 2000-an, ketika masyarakat Indonesia mulai membuka diri terhadap keberagaman budaya. Generasi muda yang penasaran mulai mendekati dunia seni tradisi ini. Mereka belajar membuat boneka, mempelajari teknik memainkan wayang, hingga menulis ulang naskah-naskah klasik agar lebih relevan dengan masa kini.
Salah satu tokoh yang cukup dikenal dalam upaya pelestarian ini adalah Ki Gondo Tjandra dari Surabaya, seorang dalang non-Tionghoa yang telah mementaskan Wayang Potehi di berbagai daerah. Ia mengajarkan bahwa seni tidak mengenal batas etnis atau agama; Wayang Potehi adalah milik bersama yang patut dijaga.
Inovasi di Era Modern
Kini, Wayang Potehi kembali hadir dalam bentuk yang lebih segar dan dekat dengan generasi muda. Pertunjukan tidak lagi terbatas di kelenteng, tetapi juga tampil di kampus, kafe budaya, hingga festival seni. Para dalang muda menambahkan unsur musik modern, tata cahaya panggung, bahkan alur cerita kontemporer.
Beberapa grup seni juga mulai menyiarkan pertunjukan Wayang Potehi secara daring melalui media sosial dan kanal YouTube. Penonton dari berbagai daerah bisa menonton langsung dan berinteraksi melalui komentar. Kehadiran teknologi digital membuka peluang baru bagi pelestarian seni tradisi ini. Tidak sedikit pula sekolah dan komunitas budaya yang menjadikan Wayang Potehi sebagai materi pembelajaran lintas budaya.
Wayang Potehi sebagai Simbol Toleransi
Lebih dari sekadar seni pertunjukan, Wayang Potehi telah menjelma menjadi simbol toleransi dan akulturasi di Indonesia. Ia membuktikan bahwa pertemuan dua budaya besar bisa melahirkan karya yang mempersatukan, bukan memisahkan. Ketika boneka kecil itu menari di atas panggung, yang tersaji bukan hanya kisah dari negeri jauh, tetapi juga potret keberagaman bangsa yang saling menghargai.
Melalui Wayang Potehi, kita belajar bahwa warisan budaya tidak harus dikurung dalam batas asalnya. Ia bisa tumbuh, beradaptasi, dan menemukan bentuk baru yang lebih hidup. Di Surabaya dan Semarang, suara musiknya masih menggema, mengingatkan bahwa di balik setiap tradisi, selalu ada semangat manusia yang ingin mempertahankan makna dan kebersamaan.
Menjaga Nyala Budaya
Wayang Potehi bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan warisan hidup yang terus berdenyut di tengah zaman modern. Keindahan dan nilai-nilai yang dibawanya menjadi pengingat bahwa budaya adalah jembatan antar manusia. Selama masih ada yang mau bercerita dan mendengarkan, Wayang Potehi akan terus hidup, menari di antara masa lalu dan masa depan.
Di panggung kecil yang penuh warna itu, boneka kain menunduk memberi salam. Dan dari balik layar, suara dalang berbisik lembut—seolah mengingatkan kita semua, bahwa setiap budaya, sekecil apa pun, pantas untuk dijaga dan dirayakan.